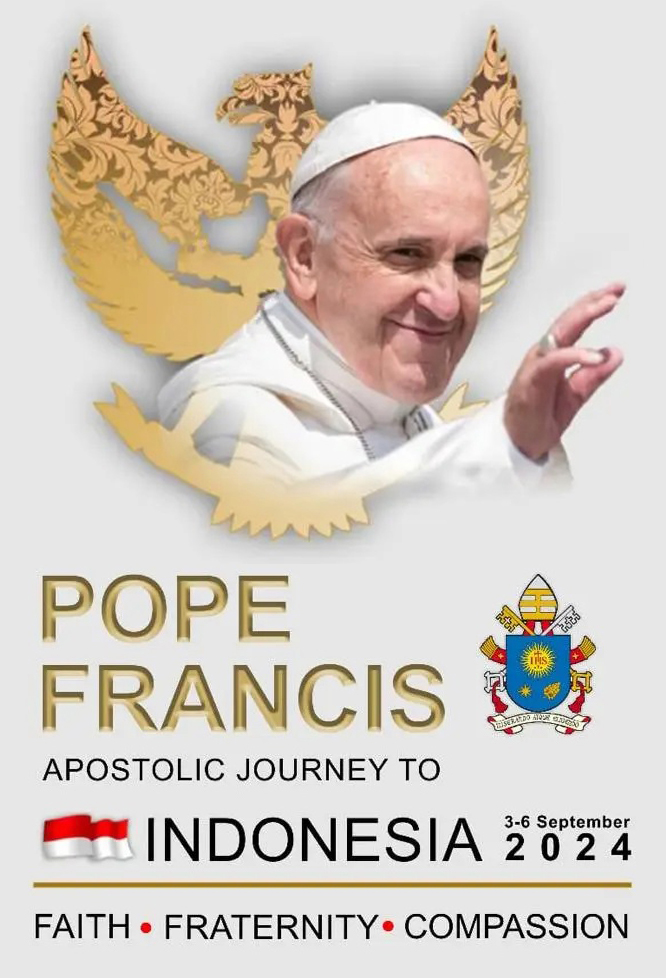HIDUPKATOLIK.COM – DALAM merespons komentar tentang tayangan kurang positif di salah satu media sosial baru-baru ini, seseorang menulis begini “Ini hanya hiburan. Kalau Anda tidak suka, silahkan skip. Tidak perlu Anda berkomentar aneh-aneh. Akun/room ini punya saya. Suka-suka saya mau bikin konten apa”. Ada pula yang berkomentar terhadap satu konten tentang tayangan yang memperlihatkan seseorang pada saat berdoa mengucapkan kata-kata yang tidak santun di satu media sosial dengan menulis begini “Ini hanya hiburan di media sosial. Jadi tidak perlu ditanggapi secara serius”.
Menarik mencermati reaksi dua orang di medsos di atas. Yang jelas, dalam komentar itu tercermin bagaimana gambaran atau pemahaman nitizen tentang makna ruang publik. Pertanyaan yang relevan kita angkat berkaitan dengan hal tersebut: apa sesungguhnya makna ruang publik bagi kehidupan manusia? Apakah ruang publik memiliki makna etis? Bercermin dari dua komentar dua nitizen demikian, tergambar dengan jelas bahwa terjadi degradasi makna ruang publik, bahkan nihilisme etis ruang publik. Ruang publik dalam paham demikian merupakan tempat yang bebas dari nilai etis.
Mengidiomkan pandangan Milton Friedman, ruang publik dipandang sebagai tempat yang bersifat amoral. Artinya, ruang publik dipahami sebagai tempat yang lepas dari tuntutan etis seperti tanggung jawab moral dan sikap peduli kepada orang lain. Dua komentar itu seolah-olah juga bermaknakan penyangkalan akan sosialitas sebagai bagian eksistensi manusia. Di sana seolah-olah individu hadir dan terpisah dari individu yang lain, sehingga setiap individu di dalamnya boleh berbuat, berucap dan menulis apa saja dengan dorongan, bahkan pengarahan ketat dari gerakan naluri instingtual. Jelas pandangan demikian keliru total, bahkan bermuatan dehumanisasi.
Dari Makna Etis ke makna Sekular
Dalam bukunya The Fall of Public Man (2017), Richard Sennett memperlihatkan bahwa sesungguhnya ruang publik bukan bebas dari nilai etis, melainkan sarat dengan makna etis. Hal itu sesungguhnya telah tergambar dalam sejarah manusia, yang dimulai di jaman Yunani. Dalam tradisi orang Yunani, menurut Richard, pada awalnya ruang publik bersifat sakral, karena merupakan tempat setiap orang memberikan penghormatan kepada sang penguasa alam, yakni dewa dan dewi. Mereka yang hadir di ruang publik (baca: kuil) adalah orang yang berniat baik dan bermotif hati murni sekaligus berpengharapan pada kekuatan sang Pencipta. Manusia merendahkan diri di sana dan merasa diri tak berdaya.
Hal lain tergambar dalam ruang tersebut bahwa ruang demikian bukan menjadi miliki orang tertentu, tetapi milik dari semua orang yang berkehendak baik dan berharap pada pertolongan sang Kekuatan di luar manusia. Artinya, ruang publik adalah milik bersama, karena itu pula ia menuntut tanggung jawab dari setiap pribadi bagi keberlangsungan dan menjaga kekhusukannya.
Sennet lebih lanjut menambahkan bahwa para filsuf Yunani seperti Aristoteles, sesungguhnya sudah mulai merintis pemikiran secara eksplisit tentang murni dan luhurnya ruang publik seperti tergambar jelas dalam pengertian kata “politik”. Dalam benak Aristotels, sisi etimologi kata “politik” mengandung makna yang luhur itu, yakni “polis” yang artinya adalah “kota/masyarakat” dan “taia” yang artinya adalah urusan atau kepentingan. Dengan dua kata ini, kata politik bermaknakan sesuatu yang positif bagi manusia, yakni wadah untuk mewujudkan perhatian dan kepedulian kepada orang banyak.
Atas dasar inilah bagi Aristoteles, politik merupakan jalan dan sarana untuk memberikan pelayanan, yang diistilahkannya dengan “diakonia tekne”, artinya sarana untuk melayani orang banyak. Dengan pemilahan yang jelas pemimpin dengan penjaga dan penghasil sebagai tiga kekuatan dalam struktur sosial politik, Plato memperjelas tentang peran dan posisi pelayan bagi publik dengan kemampuan dasar sang pemimpin untuk melayani masyarakat, yakni mengandalkan pikirannya dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas. Di sini sekali lagi tercetus makna luhur dari politik sebagai ruang publik.
Sayangnya hakikat politik sebagai pelayanan bagi publik mengalami pergeseran. Pada masa berikutnya menurut Sennet ruang publik lebih menjadi ajang pertarungan dan pengejawantahan hasrat dan naluri kekuasaan yang justru mengorbankan manusia. Budak-budak menjadi bahan tontonan penguasa di ruang publik, sebagai pelampiasan kerakusan dan ketamakan serta ajang balas dendam para penguasa Romawi pada jamannya.
Situasi demikian di masa berikutnya diperparah dengan dampak negatif kehadiran teknologi dan sistem ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi yang didominasi dengan semangat kapitalisme ketat dan tujuan serta maksud busuk para politisi. Ekonomi menempatkan ruang publik sebagai sarana eksploitasi demi perolehan keuntangan bagi segelintir orang, sementara politik menjadi jalan untuk pelampiasan naluri berkuasa dan dominasi terhadap manusia yang lain. Meminjam Thomas Hobbes, homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi yang lain) menjadi esensi dari ruang publik.
Akibatnya, peran dan fungsi ruang publik berubah dari situasi humanisme cenderung ke barbarisme. Ruang publik hanyalah menjadi tempat para calon-calon politisi mempromosikan diri untuk mewujudkan ambisi berkuasanya, bukan untuk menjadi “pelayan” dalam masyarakat entah sebagai calon pemimpin politik, entah mau menjadi wakil bagi rakyat. Namun Richard lagi-lagi mengamini bahwa dalam hal ini kecenderungan bahwa ruang publik hanyalah sebagai sebuah instrumen bagi kepentingan diri atau kelompok tertentu.
Di akhir bukunya Richard Sennett, bahkan memperlihatkan kegalauannya terhadap perkembangan teknologi demikian, khususnya kehadiran media sosial di era digital. Selain kehilangan otonomi di dalamnya, seperti dikhawatirkan oleh Angel Marquez dalam bukunya Autonomy Lost (2024), manusia digital telah kebablasan dalam memposisikan ruang publik. Ruang publik, yang dalam hal ini media sosial, telah dianggap sebagai hutan belantara tanpa penghuni, di mana setiap orang dapat, mau, dan boleh mengumbar apa saja tanpa batasan nilai dan aturan serta rambu-rambu sosial. Rasionalisasinya adalah kebebasan atau demokrasi.
Yang ikut memperparah adalah tiadanya pemisahan antara urusan pribadi dengan urusan publik. Bahkan di sana, terjadi penjungkirbalikan antara urusan publik dengan urusan privat. Penjungkirbalikan ini justru membuat ruang publik kehilangan makna luhur dan nilai etis, karena di situ aturan dan norma tidak lagi menjadi dasar. Ruang publik justru menjadi ajang chaos, yang oleh Richard menyebutnya sebagai komunitas yang tidak beradab (uncivilized community). Ruang publik justru menjadi ajang caci maki dan tempat menjatuhkan orang lain, namun tanpa mau bertanggung jawab. Di sana yang hidup adalah anonimitas lewat akun-akun palsu yang bertebaran. Dalam kondisi demikian ruang publik mengumbar paradoksal minus, bahkan nihil tanggung jawab. Di sana ada ruang kebebasan bagi pelaku, namun pelakunya selalu berlindung di balik jargon anonimitas. Singkatnya, ruang publik menjadi tempat yang tak beradab, buah dari anonimitas nihil tanggung jawab moral itu.
Pertanyaan kita: apakah cara pandang manusia digital demikian benar? Sebagaimana digambarkan oleh Franki Budi Hardiman, dkk dalam buku Ruang Publik (Kanisius, 2017), ruang publik bukanlah space yang bebas nilai tanpa kesadaran etis, atau ruangpengejawantahan semau gua. Seperti tergambar dalam Politik Aristotels, ruang publik memiliki nilai yang luhur. Keluhurannya justru terletak pada keterlibatan setiap subjek di dalamnya. Ruang ini juga menjadi wadah pembentukan pribadi dan masyarakat. Secara lain dapat dikatakan, di ruang publik, sisi kemanusiaan dengan segala dimensinya hadir dan dilibatkan. Jadi, ruang publik adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia demi ruang publik. Ini berarti, meminjam ide N Driyarkara, ruang publik merupakan ranah, bahkan ajang humanisasi dan hominisasi. Dengan alasan ini jelaslah bahwa ruang publik bermakna sosial, etis, bahkan mengandung makna spiritual sebagaimana telah dimulai di Yunani kuno itu. Dengan demikian pula ruang publik bersifat normatif.
Dua Implikasi
Ada dua implikasi dari esensi dan makna ruang publik yang luhur demikian. Pertama, adanya muatan tuntutan etis yang kuat dalam memanfaatkan ruang publik. Setiap individu perlu menghidupkan kesadaran dan tanggung jawab moral untuk memanfaatkan ruang publik demi pengembangan kemanusiaan secara komprehensif. Dalam hal ini Maeve Mckeown dalam With Power Comes Responsibility: The Politics of Struktural Injustice (2024) menegaskan bahwa tanggung jawab moral setiap orang memberi andil bagi terejawantahnya mutu etis ruang publik, didukung kekuatan politik yang kuat dan tanggung jawab korporasi untuk menghalau ketidakadilan struktural (structural injustice) di ruang publik. Terkait dengan ini terdapat dua arah tanggung jawab moral itu, yakni ke dalam dengan menumbuhkembangkan kesadaran etis setiap pribadi untuk menjadikan ruang publik bagi dirinya sebagai tempat pengembangan nilai kemanusiaannya, dan ke luar dalam arti memberikan ruang positif bagi pihak lain untuk berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya pula.
Dalam hal mempertahankan keluhuran ruang publik, tentunya masing-masing pribadi perlu terus menerus menata ucapan, perkataan serta tulisan dalam berkomunikasi di ruang publik dengan pilihan kata-kata yang bermakna humanis. Secara lain dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberi bobot etis bagi ruang publik dalam arti sebagai wadah bagi pengembangan dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Mendukung hal ini seperti dikatakan oleh Aristoteles, perlunya retorika bahasa yang bermakna dan konstruktif bagi kehidupan dengan memaksimalkan peranserta pikiran dan hati dalam berbuat, dan berucap, serta menulis. Singkatnya, setiap orang perlu menempatkan ruang publik, termasuk media sosial, sebagai wadah aktualisasi diri, yang di dalamnya dan melaluinya setiap ia DAPAT dan BOLEH merealisasikan potensi positifnya. Dengan demikianlah ruang publik bersifat normatif.
Kedua, adanya demarkasi yang jelas antara hal-hal yang bersifat publik dengan hal-hal yang bersifat privat. Karena itu pula, dalam rangka memberi bobot etis pada ruang publik, perlu kesadaran yang tinggi untuk memisahkan apa yang menjadi urusan publik dari apa yang menjadi urusan privat. Ketika keduanya sulit dipisahkan justru ruang publik menjadi tercemari. Keduanya kehilangan identitas serta maknanya. Sebaliknya, ketika keduanya dapat dipilah secara jelas, justru kemurnian dari kedua ruang terjaga dengan baik. Implikasi lebih lanjut adalah fungsi sosial dan normatif masing-masing terjamin dengan baik.
Marilah kita memberi bobot kemanusiaan bagi ruang publik dengan menempatkannya sebagai “locus” humanisasi, terlebih-lebih ruang bagi perwujudan sikap empati dan bela rasa pada manusia. Singkatnya, kita jadikan ruang publik sebagai wadah aktualisasi diri (Abraham Maslow) dan “actus humanus” (N. Driyarkara), termasuk menghiasinya dengan pilihan kata-kata yang bermakna afirmatif dalam berkomunikasi.

Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta