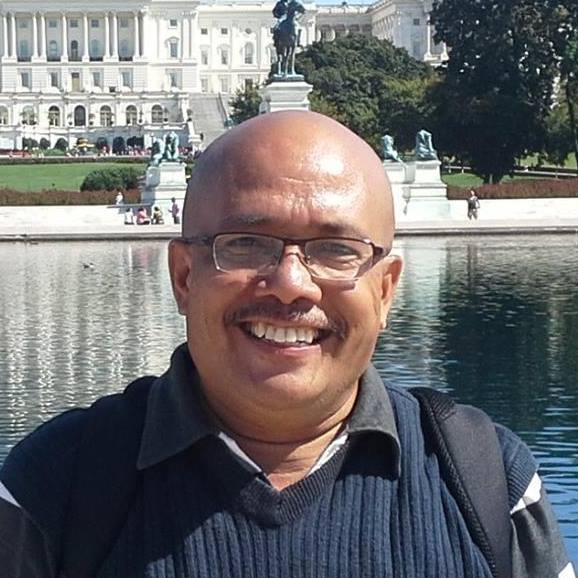HIDUPKATOLIK.COM – TEOLOGI Salib. Sebuah topik menarik, menantang. Ketika omong salib ada berbagai hal muncul spontan dalam benak kita. Tatkala ditanya tentang salib, ada tiga hal mencolok yang muncul dengan cepat dalam ingatan: penderitaan, solidaritas sosial, dan ketakutan akan salib (staurophobia).
Yang pertama, fakta derita. Salib adalah tanda penderitaan. Ada orang di masa silam yang disalibkan. Itulah aspek historis dari salib. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tatkala kita bicara tentang salib dengan konotasi derita, maka itu terkait dengan sejarah masa silam. Ada benarnya. Tetapi tidak seluruhnya. Sebab masih ada derita lain yang berlangsung sekarang dan di sini, walau tidak berupa salib. Itu sebabnya L.Boff mengatakan bahwa teologi (salib) harus bermata ganda: “ante et retro oculata”, katanya dalam pengantar bukunya yang saya terjemahkan awal 90-an, Jalan Salib Jalan Keadilan (Kanisius: 1992). Mata yang satu melihat ke masa silam (in illo tempore, pada waktu itu). Mata yang lain melihat ke masa kini (in hoc tempore, pada waktu sekarang ini).
Mata yang terarah ke masa kini menunjuk kepada solidaritas-sosial, poin kedua tulisan ini. Ini perkara nilai, perkara orientasi-etis hati nurani. Di sini saya teringat akan gambar salib terkenal. Satu tangan Yesus tersalib dan tangan lain terlepas dan mau jatuh. Ternyata itu adalah cara sang seniman “berteologi” melalui gambar, theology in colors (imbangan theology in words yang ada dalam Tradisi Gereja). Itu adalah istilah Rublev, ahli ikon dari Orthodox Russia abad ke-15. Teologi di balik patung salib Yesus seperti itu ialah bahwa Yesus mau memperlihatkan solidaritas kendati derita. Tangan Yesus yang “terlepas” dimaksudkan bukan untuk jatuh apalagi melarikan diri dari derita. Tangan “terlepas” itu dimaksudkan untuk diulurkan kepada lian yang membutuhkan, yang mungkin lebih menderita. Secara psikologis bantuan dan solidaritas dari sesama penderita akan menjadi sesuatu yang menguatkan.
Terkait ide solidaritas-sosial psikologis dalam derita ini saya teringat akan buku F.X.Kim Chi Ha (sastrawan dan penyair Katolik Korea Selatan; kritiknya amat pedas terhadap rezim totaliter tahun 60-70 di Korea; karena itu ia sering masuk penjara dan dituduh agen komunis yang berlindung di balik Gereja Katolik. Tuduhan itu tidak benar. Ia membela diri dengan mengatakan, saya menjadi radikal karena saya Katolik. Inspirasi radikalitasnya ialah Vatikan II terutama Gaudium et Spes). Saya mengenal buku ini karena saya menerjemahkannya tahun 1989, tetapi tidak terbit. Judulnya, The Gold-Crowned Jesus, and Other Writings (Orbis Books: 1978). Banyak tulisan dia ditulis dalam penjara. Dengan bantuan seorang imam Jesuit, tulisan-tulisan itu lolos keluar tembok penjara dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan di New York.
Yesus Bermahkota Emas. Itu naskah teater. Konon di sebuah taman di Seoul ada patung Yesus. Patung itu istimewa: mahkotanya emas. Suatu hari ada pengemis yang letih dan lapar. Ia duduk dekat taman itu. Matanya terpesona melihat emas di kepala Yesus. Ia tergoda: kalau saya curi emas itu, saya bisa membeli apa saja, terutama makanan untuk laparku ini. Tetapi curi itu dosa. Tetapi kalau saya tidak mencuri, saya tidak bisa dapat emas itu. Kalau tidak ada emas, tidak ada uang. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Tidak ada makanan berarti lapar. Lapar berarti mati. Lebih baik mencuri. Ia panjat patung raksasa itu dan mengambil mahkota emasnya. Ajaib! Begitu mahkota emas itu copot, Yesus hidup dan bisa berkata-kata. Yesus berterima kasih kepada pengemis itu karena ia membebaskan diri-Nya dari belenggu emas itu. Pengemis terkejut dan takut. Ia mau lari membawa emasnya. Tetapi polisi datang dan menangkap si pengemis, mengambil mahkotanya dan dipakaikan lagi di kepala Yesus. Yesus pun menjadi patung kaku lagi. Pengemis masuk penjara.
Kim Chi Ha tidak memberi pemaknaan terhadap naskahnya. Pemaknaan tergantung pada pembaca dan penonton. Karena itu menurut saya, makna terpenting ialah bahwa kemewahan seperti emas akan lebih berguna bagi karya sosial-karitatif daripada karya decorative sekalipun itu untuk menghias kepala patung Yesus.
Dua hal sudah dilihat: pertama, orientasi dan konotasi historis, dan yang kedua relevansi etis salib sebagai solidarias sosial. Kedua hal itu sangat bermakna. Walau ada makna yang mendalam dan positif seperti itu secara etis dan historis, ternyata masih ada yang takut akan salib (staurofobia). Ini poin ketiga. Salib adalah ancaman bagi eksistensi mereka. Dari rasa takut itu muncul wacana negatif, hatespeech tentang salib. Hal itu berlangsung sejak Perjanjian Baru hingga sekarang ini. Mungkin fenomena takut akan salib mengganggu kaum beriman. Tetapi bagi saya patokannya jelas. Yang menentukan bukan wacana luaran, melainkan wacana dalaman, yaitu bagaimana saya sebagai orang beriman memaknai salib. “Kami memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah” (1Kor. 1:23-24).
Untuk mengakhiri tulisan ini saya kutip lagu tradisional penghormatan salib Jumat Agung. Dulu dinyanyikan dalam Latin. Sekarang dalam Bahasa Indonesia; mungkin tidak banyak yang tahu. Saya kutip baris awal untuk memperlihatkan betapa salib mendapat tempat dalam seni liturgis: Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nula talem silva profert, fronde, flore, germina. Dulce lignum, dulce clavos, dulce pondus sustinet. Terjemahan Puji Syukur 509: Salib suci nan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi daun, bunga, buahnya. Kayu, paku bahagia memangku pangkal hidup.