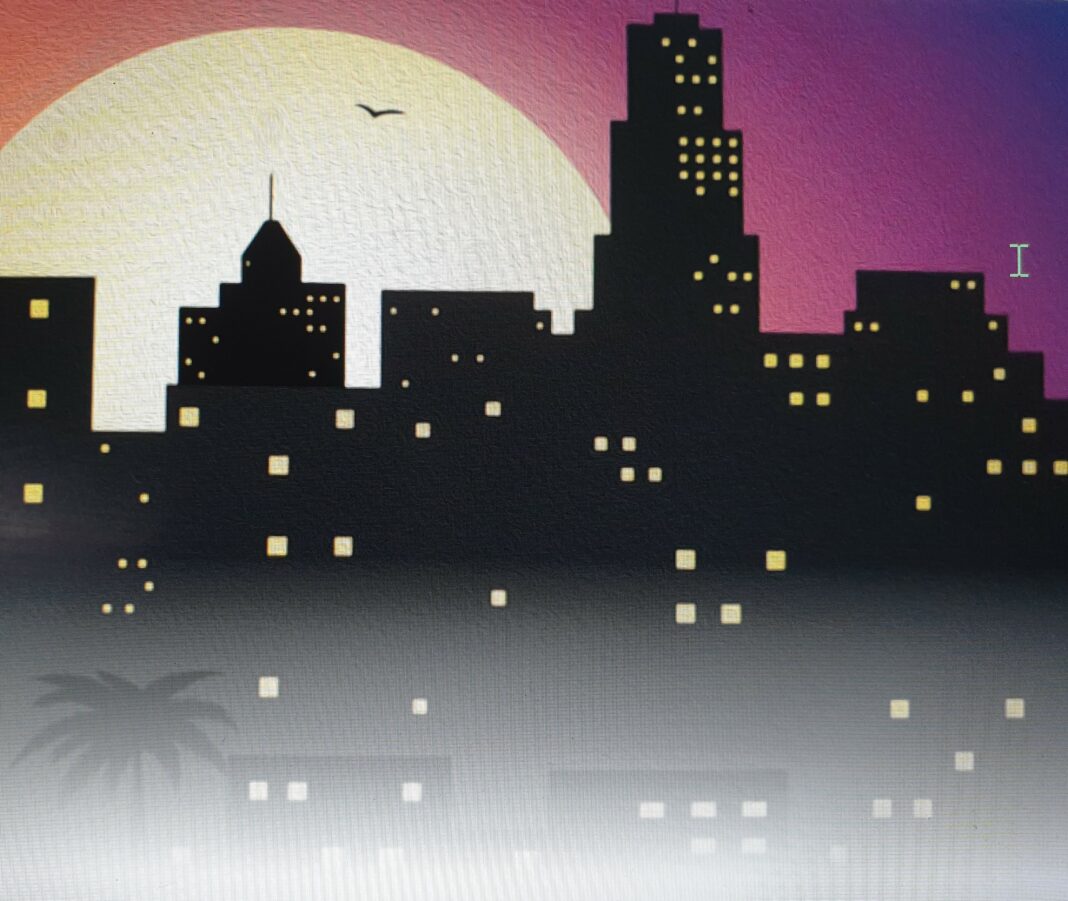HIDUPKATOLIK.COM – MUSEUM of Arts and Design, di pertengahan bulan Desember. Malam hari menyisakan dingin nan luar biasa. Sepanjang Colombus Avenue. Berpendar lampu-lampu megapolitan. Teringat ’Seribu Kunang-Kunang di Manhattan’ milik Umar Kayam. Terdengar dalam imajinasi piringan hitam ”New York, New York” versi Andy William milik bapakku yang konon kata bapak alat pengungkap cinta pertama kepada ibuku.
Kakiku menelusuri sepenggal jalan yang dipenuhi kelab-kelab malam. Lelaki dan perempuan bergerombol mengusir dingin malam dengan segelas vodka, sekerat steak dan bunyi saxophone yang ditiup penuh perasaan oleh musisi jalanan. Tepat di belakang pemberhentian bus. Ada taman yang disulap menjadi panggung menyambut Natal. Di panggung, terdengar O Holy Night didendangkan nan megah oleh kelompok paduan suara murid-murid sekolah.
Bukan panggung Natal tujuanku. Dua ratus meter dari panggung Natal, Fordham University tampak terang benderang. Tepat di sisi kiri Fordham University ada housing untuk mahasiswa. Kamar no 19 C. Kupencet bel. Terdengar dekak-dekak kaki dari balik pintu housing. Sedikit pintu terbuka. Si penghuni housing melongokkan kepala. Sejenak terpaku di hadapanku. Bibirnya menyebut nama Sang Pencipta.
Tanpa kompromi si penghuni housing menarik tubuhku. Sejurus berikut aku sudah dibanting di atas sofa empuk. Dan ini yang selama lebih dari sembilan tahun kutunggu-tunggu. Bibir si pemilik apartemen berkeliaran menyerang wajahku.
”Maaf…maaf….” perempuan ayu tiga puluh dua tahun bernama Alexandra Gitanjali Oey menatap tajam wajahku,”Aku terlalu agresif!”
”Kau agresif?!” aku bertanya. Sebelum Gita — nama panggilannya — menjawab, gantian aku bereaksi. Kudekap erat tubuh Gita. Kusibak daun telinganya. Ada dua anting bertengger di sana. Satu merah, satunya lagi biru, ”Aku lelah mencarimu,” kubisikkan kata-kata lembut di telinga Gita.
Pertemuan luar biasa setelah lebih sembilan tahun tidak bersua. Pada telinga Gita masih terpasang dua anting yang aku belikan di kawasan Malioboro. Apresiasi diriku akibat dia terlalu pintar. Menuntaskan kuliah empat tahun dengan predikat summa cum laude di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Lebih hebat lagi, Gita bukan mahasiswi kutu buku yang hanya menghabiskan waktu belajar dikamar kos. Gita aktivis mahasiswa. Garang di podium-podium diskusi antarmahasiswa. Tajam dalam merangkai kalimat menjadi tulisan yang tersebar di media-media kampus.
Hanya semua menjadi lenyap ketika tangan Gita ada dalam genggaman tanganku. Gita tak ubahnya mahasiswi cantik kebanyakan. Lembut dan membuka diri lebar-lebar hatinya untuk diriku. Kamar kos Gita yang relatif luas di Jalan Gejayan Yogya. Ruang depan ada meja belajar, kursi dan rak-rak berjejal aneka buku. Kamar belakang, berpintu rapat. Di situlah Gita mengistirahatkan tubuhnya. Di ruang depan, aku selalu duduk di kursi sebelah kanan. Tepat di depan rak-rak buku. Gita menyajikan seduhan kopi dari kampungnya, Gunung Dempo Pagar Alam Sumatera Selatan.
”Ayahku pengusaha kopi di Pagar Alam. Sejak muda ayah dari Palembang merantau ke Pagar Alam. Berdagang kopi mulai dari teras rumah yang di sewa ayah. Lalu ayah bertemu orang asli Pagar Alam, ibuku,” Gita menuturkan masa lalu keluarganya.
”Ibumu asli orang Pagar Alam. Kau berkulit putih, bermata sipit. Kok bisa?” aku bertanya. Kucecap kopi Gunung Dempo seduhan Gita yang memang selalu memikat lidahku.
”Dulu ketika SMA pas pelajaran sejarah, kamu tidur ya Gung?” Gita menatapku. ”Di Palembang, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya itu banyak bercampur darah orang lokal dan Tionghoa. Ibuku salah satu keturunan campuran itu yang tinggal di Pagar Alam.”
”Gitanjali? Ini nama sansekerta yang dipakai orang-orang Jawa,” kutanya lanjut asal-usul namanya.
”Di Pagar Alam banyak komunitas orang Jawa. Bahkan perkebunan teh disepanjang Gunung Dempo itu, mayoritas dihuni orang-orang Jawa. Ayah suka nonton ketoprak yang dimainkan orang-orang Jawa. Bahkan setahun sekali ayah mengundang dalang dari Jawa untuk merayakan panen kopi. Makanya namaku Gitanjali. Lucu ya, nama Gitanjali memiliki marga.”
Alexandra Gitanjali Oey nama lengkapnya. Gita nama jejuluknya. Menjadi teman terbaik bagiku untuk bercerita. Bertutur apa saja. Mulai dari teknologi pangan, kisah-kisah Yunani kuno, hingga konser musik yang digelar U2. Gita juga teman terbaik untuk menyambangi 21 menonton film terbaru besutan Quentin Tarantino atau akting memikat Natalie Portman.
Lalu, nun jauh menyeberang lautan. Pada kampung halaman Gita. Ayahnya mencalonkan diri dalam pilkada. Sebagai pengusaha kopi yang mengakar di masyarakat. Dukungan luas dari berbagai pihak. Menggandeng tokoh lokal sebagai wakilnya. Ternyata pertarungan berjalan sangat keras. Menuju brutal. Dua belas tahun pintu demokrasi terbuka akibat runtuhnya Orde Baru, memunculkan mahkluk yang tidak kalah mengerikan, sektarian.
Latar belakang ayah Gita menjadi sasaran empuk sektarian. Tidak hanya serangan verbal yang brutal. Lebih dari itu. Gudang kopi, penanda kebanggaan ayahnya karena didirikan dari titik nol, dibakar massa. Ayah Gita kecewa. Keguyupan dirinya dengan petani kopi. Kedekatan dirinya dengan komunitas-komunitas lintas agama dan suku. Menguap hanya karena syahwat politik.
Kekecewaan ayah Gita tidak tertahankan. Semua kekayaan dijual. Orangtua Gita memutuskan bermigrasi. Ke negeri nun jauh, Amerika. Gita yang kebetulan sudah lulus kuliah mengikuti orang tuanya. Kakak semata wayang Gita, Alexander Oey tidak ikut bermigrasi. Justru memutuskan menjadi politisi.
”Kakakku memang keras kepala. Kejadian yang menimpa ayah justru membelokkan profesinya. Melepas jadi eksekutif perusahaan multi nasional. Ikut partai dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pusat. Kakak memilih Pagar Alam sebagai daerah pemilihannya. Kakak ingin menunjukkan bahwa Pagar Alam itu toleran. Pagar Alam itu indah. Pagar Alam itu Indonesia mini,” telepon dari Gita sebulan setelah ia tinggal di Amerika. Ternyata itu telepon terakhir darinya. Sejak itu, Gita tiada berkabar lagi. Semua nomer kontak dan emailnya berganti.
Sembilan tahun Gita hilang dari layar edarku. Hingga dari jejaring sosial kutemukan sosok dirinya. Jejak-jejak digital miliknya kemudian menuntun diriku ke tempat ia tinggal. Malam ini, aku sudah meringkuk di tempat tinggalnya.
”Malam nan indah ini, kita habiskan menelusuri Central Park. Menjelang Natal, Central Park sungguh romantis dengan lampu-lampunya,” Gita mengambil jaket tebalnya. Meraih tanganku. Central Park di bulan Desember memang memikat. Salju yang menempel pada pepohonan. Disorot aneka lampu dari berbagai sudut. Pernak-pernik Natal beraneka rupa. Angin Desember yang sangat dingin. Tiada yang dapat menolong mengusir dingin kecuali semakin rapat mendekap tubuh Gita.
”Kedai kopi terenak di Central Park,” kata Gita ketika di depan kami ada antrian orang-orang. Lalu Gita ikut mengantri. Dua kopi hitam. Ditambah satu kentang panggang dan dua potong donat. Menemani kami duduk di bangku panjang Central Park.
”Di New York pada Musim Dingin. Sedang apa kamu di sini, Gung?” Gita membuka percakapan. ”Perusahaan digital global di mana aku bekerja, menempatkan diriku di sini. Sudah dua tahun ini aku di Amerika. Dua puluh satu bulan aku tinggal di Seattle. Tiga bulan ini aku pindah ke New York.” Aku seruput kopi untuk menghangatkan tubuh. ”Sembilan tahun tidak bersua. Kau kuliah lagi?”
”Enam tahun ini aku bekerja di litbang perusahaan pangan. Guna menambah ilmu, tahun ini perusahaan memberi kesempatan padaku ambil doktor.” Gita merapatkan tubuhnya kepadaku.
”Keluargamu kamu ajak sekalian ke sini?” tanyanya.
”Sembilan tahun aku mencoba merangkai hubungan dengan beberapa wanita. Ternyata terlampau sulit bagiku untuk melupakan dirimu. Aku masih seperti dulu. Sendiri.” Kutatap wajah Gita. ”Kamu sendiri?”
Gita tiada berani menatap wajahku. Pandangannya nanar jauh ke depan. Menatap pohon-pohon nan rindang di Central Park. Dia melihat pergelangan tangannya. Jam delapan lebih tiga puluh tiga menit. ”Gung, aku harus ke rumah temanku. Kita ke sana.” Gita mengangkat tubuhnya. Kuikuti. Kami kembali menelusuri Central Park. Menuju 67th street. West Street Apartment. Kamar nomer 19 C. Gita mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, sekonyong-konyong anak berumur tiga tahun berlari ke arahnya. Gita menyambut si anak kecil. Memeluknya. Menggendong dan mencium berkali-kali.
”Agung, ini anakku. Namanya, Christie,” kata Gita menatapku. Christie, anaknya, tetap dalam gendongannya.
”Anakmu?!” aku nyaris berseru. Namun suaraku tersumbat. Napasku memburu, naik turun tidak beraturan. ”Ini rumah suamimu?”
”Tepatnya, rumah adik suamiku. Suamiku meninggal dua tahun lalu, ketika Christie baru berumur setahun.”
Seketika kutatap wajah cantik Christie. Kuulurkan tangan kearahnya. ”Christie, ayo ikut ayah.” Christie sejenak menatapku. Ragu-ragu.
”Christie. Ini ayah.” kuulangi lagi perkataanku. Mungkin ini sebuah campur tangan Ilahi. Christie melepaskan diri dari dekapan Gita. Menyambut uluran tanganku. Christie ada dalam gendonganku. Gita terpaku. Menatapku tajam. Aku tahu ada gumpalan air dimatanya.
Aku membuka telepon genggam. Tersambung dengan sosok yang aku kagumi sepanjang hayat, ibu. Nun jauh di Yogya, ibu menerima kabar dariku.
”Ibu, keputusanku berubah. Natal ini aku pulang. Pulang bersama Gita. Pulang membawa Christie.”
Oleh A.M. Lilik Agung
Lippo Karawaci, 27 November 2020