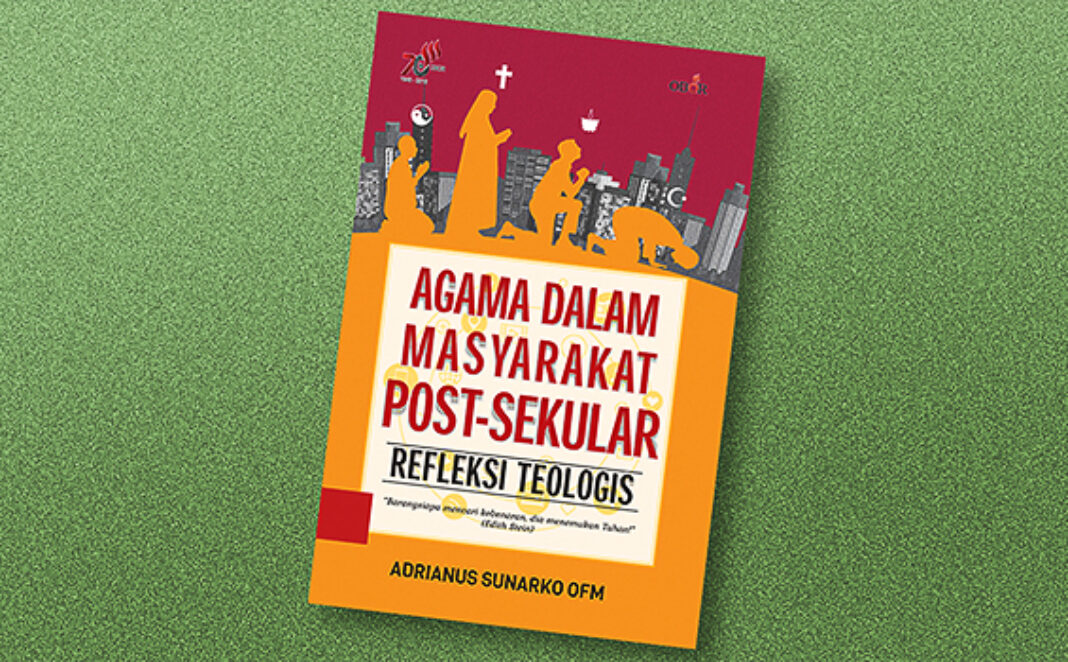HIDUPKATOLIK.com – Suasana ruangan penjara itu sepi pengunjung dengan jendela-jendela yang dibiarkan terbuka. Sementara lorong gelap menjorok ke tengah wilayahnya, memiliki bilik-bilik berpintu jeruji dan berbaris sampai ke ujung. Minim cahaya sepertinya minim kehidupan, meski di tempat itu kehidupan justru menunjukkan cahayanya. Ketika suasana semakin gelap, cahaya justru semakin luas dapat berpendar ke segala arah. Sebagaimana dalam hidup panggilan ini, aku semakin menemukan kemurnian semakin meluap saat joroknya pemikiranku menghantam batin, membutakan mata hati dan melunturkan semangat hidup. Aku semakin menemukan Tuhan justru dalam ketakutanku pada kekuatan dunia yang semakin menghimpit kebaikan kepada sesama manusia.
Setelah pos penjagaan lewat, aku melangkah memasuki ruangan penuh jendela di dinding. Terali jendela menunjukkan kehidupan penghuni yang terus dipagari bunyian alarm. Ya, seperti sekarang ini, ketika baru kuayunkan tiga langkah ke dalam ruangan, bunyi alarm menggema hingga ke sudut gendang telinga. Derap langkah tak beraturan muncul dari arah lorong gelap, semakin lama semakin dekat dan memantulkan bayang-bayang manusia. Entah bagaimana dapat kugambarkan perasaanku saat itu, ada ketengangan antara ketakutan manusiawiku menghadapi mantan pecandu kejahatan, tetapi ada juga niat membawa wajah Allah yang kuimani dalam hidup perutusanku ke tempat ini. Wajah legam nan suram berbaur dengan antulan cahaya dari jendela-jendela. Sambil menukik senyum di wajah, aku mencoba menenangkan diri, bersikap diam dan selembut mungkin membangun ancang-ancang, kalau-kalau mereka berubah garang.
“Selamat sore, Pak! Om! Oppung!” kucoba mengumpul semua keberanian untuk menyapa mereka satu per satu. Mereka tertegun, ada juga yang heran, ada yang tertawa singkat, tapi yang lebih memberiku rasa penasaran besar adalah lelaki di barisan paling belakang yang tak memunculkan ekspresi apapun. Ia tidak menghiraukan aku sama sekali ketika tubuh mungilnya melaju dari hadapanku.
Setelah semua orang berkumpul di ruangan penuh jendela itu, perkenalan menjadi hidangan pembuka di pertemuan pertamaku dengan mereka. Dengan jubah cokelat bertalikan ikat putih di pinggang, aku memulai dengan sedikit lelucon ringan, siapa tahu mereka bisa lebih berwajah manusiawi terhadap orang yang sedang berbicara ini. Hampir semua orang ikut tertawa membalas leluconku kecuali si wajah datar. Leluconku tak bisa mengangkat kepalanya sedikit pun, apalagi menukikkan senyum di wajahnya.
“Maaf, Pak! Boleh saya tahu siapa nama Bapak?” kataku sambil mendekatinya.
“Dimas!” jawabnya ringkas.
“Apakah Bapak baru di sini?”
“Hmm….”
“Oh begitu. Kalau begitu kita sama ya, Pak! Saya juga masih baru, jadi mohon perhatiannya!” sanggahku, mencoba bisa meraih lebih banyak jawaban. “Ya.” Lagi-lagi jawaban ringkas. Biarlah, kataku dalam hati. Kulanjutkan pertemuan dengan ibadat singkat diikuti diskusi ringan mengenai apa saja yang menurut kami dapat memberi keringanan pada ketegangan ini.
“Oke, Bapak-Bapak! Hari ini cukup sekian pertemuan kita. Saya ingin menandaskan satu hal, bahwa saya datang bukan sebagai pengunjung asing, melainkan sebagai saudara. Anda sekalian adalah saudara saya dan saya ingin mengenal semua saudara saya. Jadi, tolong terimalah saudaramu ini!” Kata-kata itu meluncur tanpa izin dahulu. Keberanianku ciut mengungkapkan apapun ketika menyadari semua ucapanku. Menunggu reaksi mereka mungkin pilihan terbaik.
“Ya!” suara itu datang dari si wajah datar. Hanya dia, sedangkan yang lain mematung. Sebelum aku pulang dan mereka perlahan berpaling menuju lorong gelap, tanganku merogoh saku jubahku. Kutemukan rosario fosfor kecil yang selalu kupakai di mana pun aku dapat berdoa. Kuberi itu kepada si orang wajah datar, sambil tersenyum tulus kusarankan dia memakainya bila sedang merasa sendiri. Entah dia tahu maksudku atau tidak, wajahnya akhirnya bisa mengguratkan seulas senyum meski tipis.
Pengalaman hari itu menjadi bahan permenunganku mengenai orang-orang yang biasa dikucilkan dari masyarakat. Setelah melewati masa menegangkan hari itu, aku semakin bisa berbaur dengan mereka setiap kali aku datang. Hingga akhir masa pelayananku di penjara itu, aku menjadi bagian dari kehidupan mereka di dalam ruangan jendela jeruji.
Kadang mereka bertanya untuk apa menjadi seorang pelayan seperti diriku, kalau toh harus hidup sendiri tanpa isteri dan minus pemasukan. Untuk apa juga mau mengunjungi orang-orang yang telah dibuang dari masyarakat karena sebuah kesalahan, kesalahan yang menghapus semua taburan kebaikan sepanjang hidup. Mereka tak bisa menerima kalau akhirnya bisa mendengar kata saudara dari seseorang yang tidak pernah hidup bersama dengan mereka di dalam pengucilan itu. Hah! Meskipun aku tidak mau menjawab panjang lebar dengan segudang kata dan ungkapan Injili, mereka tampaknya bisa mengerti. Ternyata kasih dalam perbuatan lebih bersuara daripada kata-kata.
Rekomendasi baik dari kepala penjara membuat pembimbing rohaniku puas. Aku lulus dengan baik dari rumah pendidikan dan melanjutkan hidupku pada karya kerasulan yang lebih luas lagi. Dalam setiap tugas yang kukerjakan, aku hanya bisa mengandalkan apa yang kuteladani dari Santo Fransiskus dari Assisi. Ia selalu membawa cinta kepada setiap orang yang ia temui, sambil menyapa mereka dengan sentuhan kasih yang tulus, bahkan kepada orang yang telah merampoknya.
Meski sudah bertahun-tahun aku tidak lagi ke penjara itu, aku tidak bisa menghilangkan kenangan berharga di penjara itu. Kini, aku akan menghadapi orang-orang pinggiran di batas kota. Modal pengalaman telah kusiapkan, bahkan untuk situasi ekstrem setingkat dewa. Itu kuterima dari pengalamanku di penjara. Aku tidak bisa merasakan takut dan gentar yang lebih besar dibanding bertemu para narapidana. Namun, di daerah pinggiran sarat kaum pluralis ini, aku belum yakin akan sukses menjadi saudara mereka. Tidak ada tuntutan lebih dari perutusan ini selain menjadi saudara bagi semua masyarakat, cukup hidup dan bertindak sebagaimana layaknya seorang Kristen yang menghidupi Injil tanpa harus berkat banyak mengenai Tuhan. Tampaknya itu mudah, tetapi sangat sulit bagi duniaku saat ini. Maksudku, menyuruhku menjalankan misi ini seperti menanti buah dari pohon yang kehabisan daun. Semangatku layu dan kering.
“Pokoknya, kamu jalani saja, Tuhan yang akan menyirami kekeringanmu itu!” kata rekan imamku.
“Tapi aku tak bisa. Bagaimana aku bisa melihat mereka sebagai saudara bila aku sendiri terus diperlakukan seperti ini? Seharusnya sekarang aku berada di paroki, bukan malah diutus ke oran-gorang pinggiran di sana. Kamu tahu kan kalau di sana sangat sedikit orang Kristen.” Darahku memuncak menerima keputusan pimpinan. Sebulan setelah ditahbiskan menjadi seorang imam, aku ditugaskan ke pinggiran kota.
“Bagaimana pun ini keputusan pimpinan kita. Ini kesempatanmu menunjukkan ketaatanmu, Saudara!”
Bayangan lorong gelap penjara muncul di hadapanku. Di ujung lorong itu, ada diriku sedang berdiri beku, berwajah pilu membiru. Cahaya dari seberang lorong tidak sanggup menjangkau wajahku yang terlalu dalam berada di kegelapan. Semakin lama, wajah suram semakin gelap menindih wajahku, kelam meninggalkan sisa-sisa harapan yang semakin pupus.
“Awas, Pak!” suara itu datang. Tapi semua tetap semakin gelap.
“Pak! Pak!” aku masih bisa mendengarnya. Mungkin begini rasanya jika menjadi si wajah datar di penjara itu, hanya bisa melihat percikan cahaya dari kegelapan.
“Bapak tidak apa-apa?” wajahnya sekarang tampak lebih jelas, oriental dengan hidung semi-mancung. Ingatankuberbisik. Aku baru saja jatuh dari seperda motor karena menghindari seorang anak kecil yang berteriak ke arahku. Tubuhku terbaring di pinggir aspal jalan, dua meteran dari sepeda motorku yang terjungkal di parit jalan.
“Oh, saya baik-baik saja, Dik!” jawabku singkat menahan sakit di kepala.
“Hei, Bapak!” Salah seorang dari kerumunan orang di sekelilingku berteriak. “Kalau lagi mabuk, jangan bawa motor!” katanya.
“Bapak ini bagaimana! Jawab dong, Pak! Jangan hanya diam! Bagaimana kalau anak ini tadi mati!” orang itu semakin tinggi suaranya. Orang lain di situ seperti ikut tersengat nurani melihatku hanya diam membisu. Aku masih diambang kesadaranku, apakah ini nyata atau ini hanya khayalan saja?
“Bapak-Bapak, sudah, sudah. Saya tidak apa-apa!” anak-anak yang tadi pertama kulihat wajahnya berseru dengan suara
gantung.
“Tidak, Dik! Lebih baik dia dilaporkan ke polisi!” Bapak tadi berkata lagi.
“Pak! Dia ini kerabat saya. Dia saudara ayah saya yang datang dari kota! Jadi, biar ini kami selesaikan bersama saja!” kata anak itu. Aku tak berani mengambil sikap, takut gegabah.
“Hmmm….terserahmu lah, Dik! Yang penting dia tahu kalau ini salah.” Perlahan kerumunan itu memudar kembali mengerjakan kegiatan mereka. Matahari sore itu menimbulkan rasa perih di luka kepalaku. Aku meringis tapi tak mau dilihat sinis, sebab aku yang membawa sepeda motor dan aku pula yang terluka. Anak di depanku ini tampak baik- baik saja. Tapi tunggu dulu, kataku membatin.
“Dik, maafkan saya ya! Saya tadi sedang melamun. Terima kasih pula karena berpura-pura menganggap saya saudara ayah kamu.” kataku.
“Tidak, Pak! Saya tidak berpura-pura! Bapak betul merupakan saudara ayah saya. Ayah saya itu dulu dipenjara karena mencuri di sebuah toko emas. Katanya ia sudah tidak sedih lagi saat berada di penjara ketika memikirkan saya dan ibu. Ia bercerita mengenai seorang saudaranya yang memakai baju cokelat berikat tali putih di pinggangnya, persis seperti yang bapak kenakan saat ini. Katanya, saudaranya itu telah memberinya cahaya untuk menerangi ruangan penjara yang sangat gelap. Jadi ayah tidak pernah takut kehilangan kami lagi.” Anak itu bercerita minim keraguan. Dagunya terangkat menandakan bahwa ia tidak malu menyebut ayahnya pernah mendekam di penjara.
“Boleh saya tahu siapa nama ayahmu, Dik? Di mana dia sekarang?”
“Namanya Dimas, Pak! Ia sekarang ada di bengkel, bekerja.” jawab anak itu. Jawaban anak itu membawaku kembal ke lorong penjara yang gelap itu. Kini, dim tengah kegelapan itu, wajah Dimas tampak bercahaya. Ia tersenyum dengan seuntai rosario menggantung di tangannya. Aku tersadar sekarang. Perjuanganku selama ini tidak pernah disapu kesia-siaan. Panggilanku ini membawa cahaya bagi semua orang bila aku sendiri bisa melihat cahaya itu, cahaya cinta Allah yang hadir bagi semua orang. Debu jalanan melekat di sekujur tubuhku, tapi aku tak peduli lagi. Kini, yang kupedulikan hanyalah menjadi saudara bagi masyarakat ini, berlumurkan tindakan nyata yang lebih berbicara dari guratan cerita.
Cok Motung Manurung
HIDUP NO.47 2019, 24 November 2019lapas