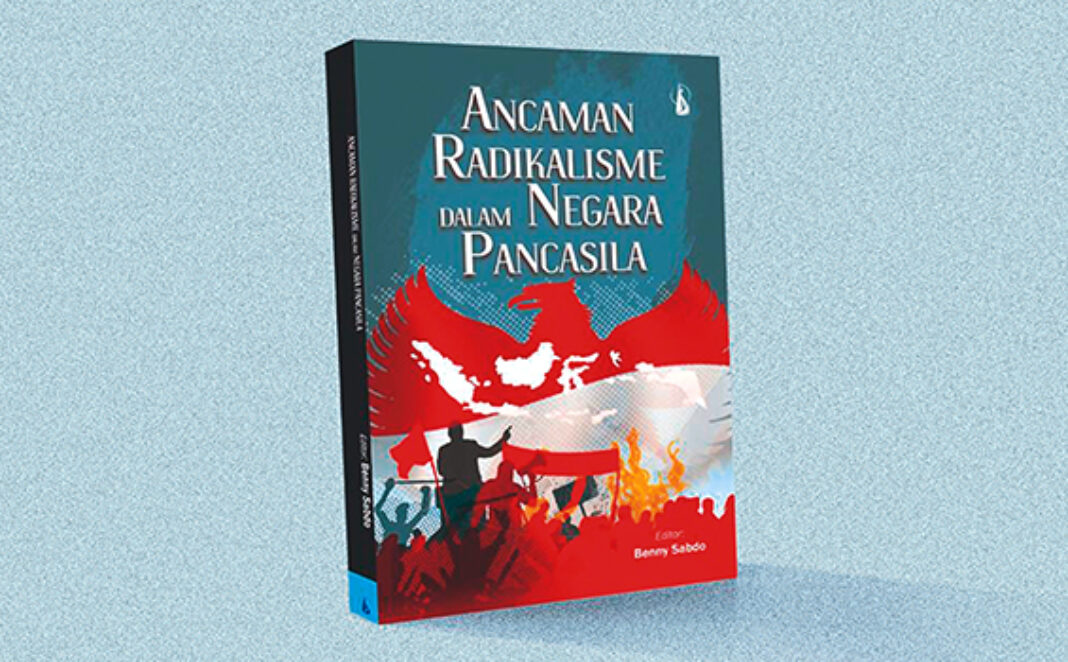HIDUPKATOLIK.com – Senja yang disepuh sinar surya keemasan mengantarku pulang ke Jakarta. Empat tahun aku bermukim di jantung kota Paris untuk menempuh studi Performing Art. Perlahan pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bapak dan Ibu sudah menantiku. Segera kami bertemu. Kupeluk mereka berdua dengan rindu yang lama terpendam.
***
“Bapak dan Ibu bangga denganmu Galih. Kamu bisa lulus kuliah tercepat dengan predikat cum laude. Meski dulu Bapak ingin kamu jadi dokter spesialis anestesi seperti Bapak dan kamu menolaknya, akhirnya Bapak bisa menerima setelah Bapak tahu kamu bisa berprestasi,” Ibu membuka percakapan kami di meja makan.
“Galih, agar kemampuanmu di bidang penyutradaraan makin meningkat, Bapak ingin kamu kuliah lagi ngambil S2 di Eropa atau di Amerika. Jangan kecewakan Bapak lagi untuk kedua kalinya,” Bapak mengultimatum.
Malam merangkak perlahan. Aku termenung sendirian di kamar tidurku yang pengap. Kata-kata Bapak tadi terus terngiang. Kuliah lagi? Di luar negeri?
Aku pandangi foto hitam putih di dinding kamar. Foto itu mengingatkanku akan Pak Waluyo, guru Seni Tariku dulu di SMA. Dari dia rasa cintaku akan seni tradisi tumbuh. Dia juga penutur sejarah yang ulung.
Suatu pagi aku menyimak ceritanya tentang Bung Karno, “Ia diasingkan dari gerakan politiknya di Jawa. Lalu Belanda membawanya ke Ende, ke Pulau Bunga di Flores yang terpencil. Dari tahun 1934 sampai 1938, Bung Karno dijauhkan dari pusat kekuasaan Belanda. Ia menjalani pengasingan bersama keluarganya. Di Ende, di bawah pohon sukun, di pinggir laut dekat rumah pengasinganya, Bung Karno membiarkan dirinya dipeluk keheningan. Ia merenungkan Lima Butir Mutiara dan merumuskan nilai-nilai luhur Pancasila yang akhirnya menjadi falsafah negara Indonesia.
Di tempat ini pula Bung Karno merasakan keterasingan karena terpisah dengan teman-teman aktivis dan pengikutnya di Jawa. Lalu ia membentuk lingkungannya sendiri dengan mengumpulkan warga kelompok bawah di sekitar rumahnya yang tidak tahu politik untuk membentuk sebuah kelompok teater. ‘Kelimoetoe Toneel Club’ namanya dan Soekarno, ‘orang pintar dari Jawa’ itu menjadi sutradaranya. Mereka latihan di malam hari diterangi sinar bulan purnama.
Pemerintah Belanda memenjara fisik Soekarno di Flores. Tapi idealisme Soekarno untuk melawan penjajahan tidak pernah dapat dipenjara. Ia juga menjalin komunikasi dengan para misionaris konggregasi Serikat Sabda Allah (SVD) di Biara Santo Josef yang jaraknya tak jauh dari rumah kontrakannya.
Pater Gerardus Huijtink SVD, seorang misionaris asal Belanda menjadi sahabat Soekarno di Ende. Ia mempersilahkan Sukarno untuk membaca buku di perpustakaan di biara St. Josef. Lewat Pater Huijtink pula Soekarno memperdalam ajaran Katolik dan makin memahami toleransi hidup beragama. Pater Huijtink juga membantu Soekarno mencarikan tempat dimana drama yang disutradarai Soekarno dipentaskan di Gedung Immaculata yang jarang dipakai. Pater Huijtink pernah meramalkan bahwa kelak Soekarno akan jadi presiden. Dan memang benar, ramalannya sungguh menjadi kenyataan.”
Di ruang keluarga, setelah Bapak pulang, aku meminta waktu untuk mengatakan sesuatu.
“Pak, Bu… maafkan Galih karena akan mengecewakan Bapak Ibu lagi. Galih tidak akan mengambil kulian S2. Buat Galih kuliah S1 apalagi di Eropa sudah cukup. Galih mau memberi sesuatu untuk bangsa ini.”
“Kalau ga kuliah S2, lalu kamu mau kerja jadi sutradara di Indonesia?” Bapak tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
“Galih tidak akan jadi sutradara dan tidak akan bekerja untuk industri film.”
“Lantas kamu mau kerja jadi apa kalau tidak jadi sutradara?”
Aku terdiam sejenak.
“Galih hanya ingin jadi guru.”
“Apa? Jadi guru? Sudah sinting kamu ya? Bapak Ibumu mengirim kamu kuliah di Eropa, tapi setelah lulus, kamu hanya ingin jadi seorang guru? Apa yang bisa kamu lakukan hanya dengan jadi guru di Indonesia?” Bapak meluapkan kemarahannya. Ibu hanya terdiam.
***
Sudah satu tahun aku terpisah dengan Bapak dan Ibu, bukan untuk kuliah lagi di Eropa. Aku nekat minggat dari rumah. Dengan berbekal restu dari Ibu, aku tinggalkan Jakarta. Sekarang aku jalani hari-hariku sebagai guru SMA di tempat yang dulu Soekarno pernah jalani masa pengasingannya. Ya, di Ende. Cerita Pak Waluyo semasa aku SMA dulu tentang Bung Karno yang diasingkan di Ende membawaku ke tempat ini. Bapak masih kecewa dengan pilihanku.
Sehari setelah kejadian itu, aku nekat kabur dari rumah, setelah sebelumnya aku kontak seorang pastor yang dulu aku kenal waktu dia masih jadi frater dan bertugas di SMAku. Sekarang dia menjadi pastor pamong dan mengelola sebuah SMA katolik di Ende. Pastor Ferdinandus Hans SVD namanya. Ia lahir di Bajawa. Dialah yang mengijinkan aku mengajar Bahasa Perancis dan teater di sekolahnya.
Meski mengalami banyak kesulitan, para siswa sangat termotivasi belajar Bahasa Perancis. Aku juga mengajarkan teater, keindahan seni peran, seperti Pak Waluyo dulu pernah ajarkan. Sebagai penutup tahun akademik, Pater Hans memintaku untuk mempersiapkan dan menyutradarai sebuah drama. Minggu depan kami akan mementaskan drama itu. Pak Alfonsus, guru Seni Budaya Flores, aku daulat untuk menulis naskah drama. Dia dengan senang hati menulis cerita tradisi yang bagus tentang seorang pemuda pemburu paus yang gagah berani di Lamalera.
“Galih, bagaimana dengan pementasan kita minggu depan?” tanya Pater Hans dengan antusias.
“Semua sudah saya pastikan siap Pater.”
“Baik. Ada perubahan yang harus kita tangani secepatnya. Kita tidak akan mementaskan drama kita di aula sekolah.”
“Kenapa Pater? Apakah aula kita tidak akan cukup menampung semua penonton?”
“Saya sudah melobi pihak pemerintah kabupaten dan mereka akan memberi dukungan. Lalu saya juga sudah mendapat ijin pemilik toko buku Nusa Indah untuk dapat meminjam toko itu agar kita bisa mementaskan drama kita.”
“Oh… syukurlah. Terimakasih Pater.”
Kami akan mementaskan drama di toko buku Nusa Indah yang bersejarah. Dulu tempat ini dikenal sebagai Gedung Immaculata dimana Bung Karno dengan “Kelimoetoe Toneel Club” nya mementaskan drama.
Tak sabar aku menelfon Ibu.
“Ibu, minggu depan kami akan mementaskan drama dan aku jadi sutradaranya. Mohon doanya”
“Ibu doakan semua lancar ya. Maaf, Ibu dan Bapak ga bisa datang.”
***
Malam ini wajah Gedung Immaculata memancarkan kharismanya. Penonton sudah memenuhi semua kursi. Tirai panggung dibuka. Adegan pertama dimulai. Beberapa siswa bersenandung lagu daerah, diiringi petikan sasando. Adegan demi adegan terlajin. Dialog, iringan musik, nyayian, dan tarian merajut sebuah alur cerita yang utuh terbangun. Penonton lebur dalam rengkuhan malam yang hangat.
Seketika aku teringat Bung karno yang dulu pernah mementaskan dramanya tepat di tempat ini 80 tahun yang lalu sebagai bentuk ekspresi seni dan perlawanannya akan penindasan penjajah Belanda. Apakah ini sebuah kebetulan? Ah…. tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini. Semua pasti sudah Dia direncanakan.
Aku juga teringat Bapak. Apakah drama ini juga menjadi simbol perlawananku akan Bapak yang memaksakan kehendaknya dan tidak menerima permintaan maafku?
Satu jam pementasan telah berlalu. Aku menghela nafas lega.
“Proficiat, Galih. Drama tadi indah dan menginspirasi banyak pemuda di sini untuk makin mencintai tradisinya. Aku berharap kamu mau tetap mengajar di Ende,” Pater Hans memberiku pujian.
“Terima kasih Pater karena telah memberi saya ruang untuk mengembangkan kemampuan anak-anak.”
“Oya… ada seorang tamu dari jauh yang juga ikut menonton pertunjukan kita. Beliau ingin bertemu denganmu.”
Sesosok perempuan anggun mengenakan kebaya perlahan menghampiriku. Sosok yang tak asing lagi bagiku.
“Ibu…..!”
“Selamat Galih. Dramanya bagus. Sengaja Ibu datang untuk melihat pertunjukanmu.”
Sebelum aku sempat bercerita banyak, Ibu mengalihkan pandangannya pada seseorang yang masih duduk di kursi bagian belakang. Dia perlahan menghampiriku. Dalam diam kami saling menatap lama.
“Maafkan Bapak, Galih.”
Air mata kami segera berderai. Air mata yang membuncah karena bahagia.
***
Ende, sebuah tempat terasing memulihkan daya hidup Soekarno, Putra Sang Fajar dari keputusasaan. Ia rela menderita demi cita-cita kemerdekaan bangsa yang ia cintai. Ende akhirnya juga menyatukan dua hati yang sempat lama terkoyak, antara Bapak dan aku. Ende, sebuah tempat terpencil di Pulau Bunga juga telah memberi harapan baru akan kasih yang selalu tertaut di lubuk hati dan sanubari.
Victor Puguh Harsanto
HIDUP NO.33 2019, 18 Agustus 2019