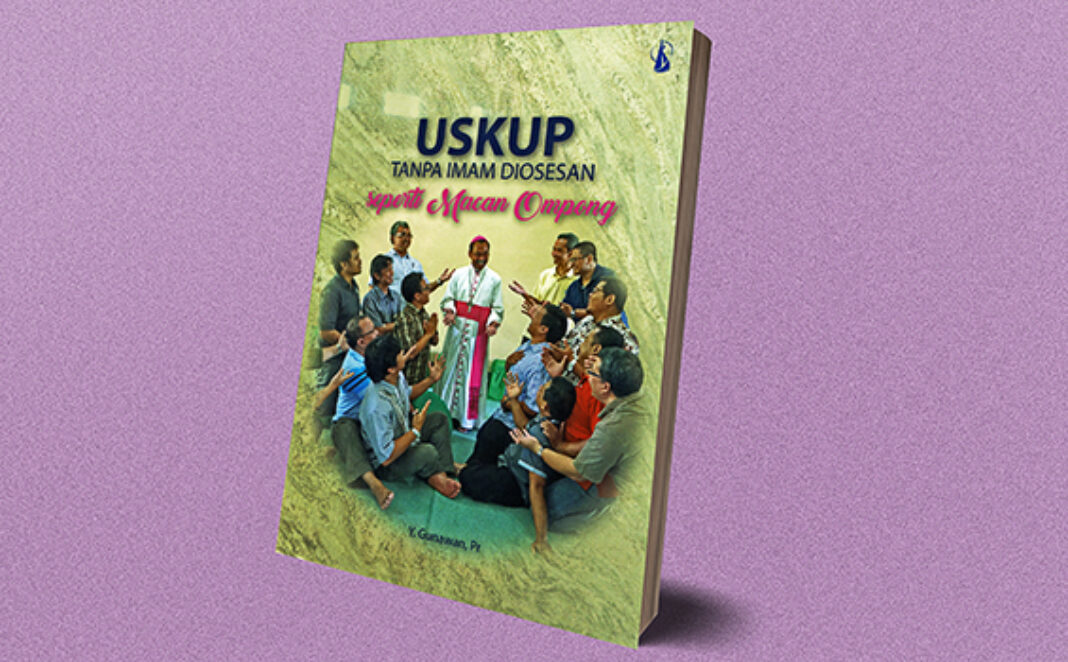HIDUPKATOLIK.com – “Apakah sejarah dan masa depan umat manusia bisa ditawar-tawar, Bu?” Tanyaku pada ibu. Wanita senja yang selalu merindukan hangatnya malam. Memang, sudah lama aku ingin mencobai ibu lewat pertanyaan itu. Hanya ingin tahu, seberapa bijak dirinya.
“Segalanya sudah ditata Tuhan,” jawabnya singkat, “tugasmu ikut saja plotnya. Itu namanya takdir,” lanjutnya kemudian.
Lalu, dengan hati-hati ibu kembali menyeruput kopi buatanku, “Enak kopinya,” pujinya.
Aku tersenyum pahit. Sepahit senja yang selalu habis ditelan malam. Makanya aku benci malam. Sangat benci! Sekarang malam hampir tiba, dan sebentar lagi ibu akan dijemput. Tentu saja, aku akan kembali berharap: semoga tubuh ibuku tak terluka oleh tombak-tombak kecil malam.
Sambil memikirkan itu aku kembali bersabda, “Berarti pemasungan umat manusia di Auschwitch, perang dunia II, peristiwa komunis tahun 1960-an, dan pemberontakan populis abad-21 adalah takdir yang telah ditetapkan Tuhan. Begitu maksud ibu?”
Mata ibu terbelalak. Diletakkannya kopi ke meja lalu kembali menatapku dengan serius.
“Kau tahu dari mana, ha anak tengik? Tuhan itu baik. Ia tak membuat penderitaan. Itu terjadi karena manusia itu bejat dan serakah,” Ibu mulai panas. Volume suaranya agak tegang. Urat di batang lehernya mulai tampak kelihatan. Ibu marah.
Tapi aku senang. Ternyata ibu mudah tersulut emosi. Ibu belum dewasa, bijaksana apalagi, begitu pikirku. Maklumlah ia baru berumur dua puluh tahun. Dan, hematku, inilah saat yang tepat untuk berdebat dengannya.
“Kalau demikian, kenapa aku dilahirkan tanpa ayah. Bukankah itu penderitaan yang paling ngeri? Bukankah ini lebih bejat dan serakah dari sekadar pemberontakan komunis, Bu? Dunia ini edan. Dan Tuhan itu memang penipu terbesar dalam sejarah umat manusia. Titik.” Teriakku dengan suara keras.
Ibu terperanjat kaget. Tanpa banyak bicara ibu bangkit berdiri.
“Tutup mulutmu, bangsat!”
Plakkk. Ibu menampar aku. Suaranya meninggi. Badannya gemetar. Matanya menyala seperti binatang yang pernah kubaca dalam kitab Wahyu, siap menerkam mangsanya. Ingin rasanya kusepak balik dirinya. Tapi aku terlampau lemah untuk melawan.
Sejak itu, ketika ibu tertunduk dan menangis, aku pergi. Tetangga-tetanggaku mulai berdatangan menyaksikan kejadian itu. Yang lain melontarkan sumpah serapah, yang lainnya lagi, menghujat.
“Dasar kafir. Manusia terkutuk. Tiada hari tanpa berkelahi.”
“Betul! Semoga di dunia akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam,” sambung yang lain disambut tawa terkekeh.
Sekejap, suasana kembali senyap. Tak ada yang berani menyentuh ibuku. Lalu, masing-masing pergi dalam diam. Dari kesunyian yang paling riuh itu, aku mengumpat dalam hati.
Dari situ, aku pun merunut sumpah : sampai usai usiaku, sekali-kali aku tidak menyesal dan tak akan pernah merasa sebagai bar-bar yang paling biadab. Sebab bagiku, itulah cara yang tepat agar suatu saat nanti, ibu bisa berkata jujur mengapa aku dinamai iblis dan ia disebut: pelacur.
***
Pertanyaan-pertanyaanku tak pernah dijawab ibu. Walau aku sudah remaja, ibu tak berani memberikan jawaban yang matang. Katanya, aku masih terlampau kecil untuk mengetahui urusan orang dewasa. Namun terus terang, aku sangat malu.
Sejak SD, aku diperlakukan tidak pantas. Aku dituduh sebagai anak iblis. Lantaran tak kuasa menahan semua omongan itu, tamat SMP, aku memutuskan berhenti sekolah. Sejak saat itu muncul niat untuk bunuh diri.
Bagaimana tidak, belum selesai dengan urusan itu, kupingku kembali dibuat panas dengan soal imanku. Guru SMP-ku mengajarkan begini : Tuhan itu, rumah yang ramah. Cintanya tak bisa ditukar atau ditakar. Kasihnya mengalir seperti sungai dan bercahaya seperti mentari. Hal itu tentu tidak demikian bagiku. Hidupku gelap. Berantakkan. Nasibku hitung-hitungan. Usahaku setali tiga uang, selalu gagal.
Dari situ, lantas bagiku, cinta Tuhan itu bisa ditakar. Cinta-Nya hanya kepada orang besar. Sebab seperti ada tertulis : orang kaya diberkati sementara orang miskin memang ganjaran bagi dirinya yang terkutuk. Dan aku salah satunya. Oleh karena itu, perihal jaminan kehidupan kekal bagi orang malang—bagiku –tak lebih dari bualan yang dinarasikan untuk menghibur hati yang sedang tersayat. Itu ciptaan orang besar untuk megekalkan ketidakdilan. Lewat orang kaya, dalilku, Tuhan mengabadikan karya ciptaan-Nya, penindasan.
Semua pertimbangan itu lantas meruntuhkan imanku. Yakni, iman yang pernah kubangun saat masih di desa. Sebab konon, aku rajin berdoa. Aku ikut misa di gereja dengan syahdu dan takwa. Aku merasa aman sebab iman yang kuamini tak satu pun kulupa. Aku pantas dibabtis, begitu kata guru agamaku.
Namun, sejujurnya itu semua tak banyak membantu. Kendati guruku berulang kali bilang: Yesus itu keturunan Daud. Anak Allah. Ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria. Sungguh, itu hanya formalitas. Demi kelancaran pembabtisan, aku berusaha untuk diam saja.
Sehabis menerima komuni pertama, aku langsung bertanya soal perbedaan antara aku dengan Yesus yang sama-sama tak punya ayah biologis. Apakah mungkin aku seperti Yesus yang dikandung dari Roh Kudus dan apakah mungkin Bunda Maria sama seperti ibuku, yang melahirkan anaknya di jalanan.
“Secara biologis memang iya, tapi jangan berpikir bahwa Yesus tidak punya ayah. Ayah Yesus ada di surga dan Dia hidup serumah dengan Roh Kudus,” ledek guruku.
“Berarti aku dikandung oleh Roh Kudus juga, dong? Sebab sejak lahir, aku tidak pernah melihat ayahku. Kata ibu, aku baru menemukannya, kelak sudah di surga. Apa benar begitu?”
“Ingat nak, ibumu bukan Bunda Maria. Bedanya dengan Bunda Maria, ibumu pelacur sedangkan Bunda Maria, wanita yang dilindungi dari dosa dan dipilih Allah. Lalu, beda Yesus dan Kau: Ia anak Tuhan tapi kau, anak iblis,” tandasnya dengan tegas. Aku merasa hancur. Aku benci jawabanya. Aku benci Tuhan. Aku benci ayah dan ibu. Entalah, aku lebih menyukai puisi dan sajak.
Dunia ini lebih baik seperti puisi. Lebih banyak metafora lebih baik. Lebih banyak imajinasi lebih tenteram. Realitas nonfiksi itu racun, kejam. Dan aku merasa ditampik olehnya. Imajinasiku berkeriapan menentukan siapa yang lebih tepat disebut iblis, aku, ibu, atau lelaki bajingan yang tak pernah menunjukan batang hidungnya itu?
***
Senja murung. Langit kerap mendung. Hujan sering turun. Petir menampar dengan cahayanya. Di sebuah ruangan sekolah, aku duduk sambil menimbang-nimbang sesuatu. Hidup atau mati, namanya.
“Pak, surga dan neraka itu ada-kah? Tanyaku kepada Pak Stau. Guru konseling di kampungku saat itu. “Dosa itu memang tiket buat masuk neraka-kah? Aku mau mati duluan. Tapi aku takut. Agama kita mengajarkan, bunuh diri itu dosa.”
Sayang, Pak Stau lebih banyak diam dan jinak. Selepas konseling, aku banyak berfantasi. Lalu menduga-duga sesuatu. Andaikata, dapat kubakar surga dan kusiram neraka sampai habis, detik ini aku mau mati. Biar bisa pastikan, apa benar aku akan berjumpa dengan ayah di surga. Karena selama hayat masih di kandung badan, hidup ini bukanlah kesempatan tetapi sebuah kesempitan. Mungkin di surga aku bisa menjadi orang sukses. Yakni status fana yang dikejar banyak orang di dunia, termasuk ibuku.
Itulah sebabnya sejak berumur tiga tahun aku dititipkan ke rumah nenek dengan alasan klasik: faktor ekonomi. Dari situ, aku ditinggal ibu ke kota. Supaya bisa menjadi sukses, katanya. Namun, situasi itu tak berlangsung lama. Karena nenek meninggal tepat beberapa bulan ibu pergi. Aku akhirnya ikut ibu ke kota.
Di kota, aku bisa mengenal esensi hidup miskin juga mengerti profesi ibu. Yakni sebuah profesi yang membuatku sulit membedakan mana dosa, mana doa, mana kota pelajar dan mana kota pelacur. Tapi syukurlah, dari situ, aku kembali memeluk teguh imanku kepada Tuhan: lewat dua hakikat ilmu hayat: licik seperti ular dan punya hati yang tulus seperti merpati.
***
Suatu malam Minggu yang sentosa, sekitar pukul 23:02, lewat jendela kamar, aku memergoki ibuku pulang diantar oleh dua perempuan sebaya. Seperti ibu, keduanya berpakaian erotis: baju terusan sekitar lima senti di atas lutut, sepatu hak tinggi, gincu menyala di sepasang bibirnya.
Tiba-tiba, sebuah mobil Avansa berwarna silver ikut menyusul lalu melesat ke area parkiran. Dari balik mobil itu muncul tiga laki-laki. Satu di antaranya merangkul tubuh ibuku lalu membawanya ke teras rumah. “mungkin itu ayahku”, aku menebak. Usai meletakkan ibu ke kursi ia melayangkan sebuah kecupan di keningnya, “jaga anak kita baik-baik, ya”. Badanku sontak gemetar saat menguping bisikan pria itu. Tak terasa aku meratap. Aku menangis tanpa air mata! Aku berusaha untuk fokus lagi. Namun pria itu lekas meninggalkan ibu dan pergi dibawa mobil itu entah ke mana.
Tak lama saat semuanya pergi, aku keluar. Kudapati ibu sudah tergeletak di lantai. Ibu terjatuh. Seirama hujan yang jatuh malam itu. Rupanya, ibu mabuk tuak. Aromanya membuatku benci sesuatu, namun bukan pencipta-Nya. Dengan tergopoh-gopoh aku mengantar ibu ke kamarnya. Lalu mengoleskan minyak ke jidat dan hidungnya biar lekas siuman.
Sebelum kutinggalkan ibu, kusempatkan diri mencium keningnya, “Ibu, aku menyangimu” batinku.
“Ah, mas cukuplah, awas nanti ketahuan anakmu,” bisik ibu.
“Ibu, ini aku, Onggi,” sahutku.
“Ha…kau?” Ibu terbelalak kaget.
R. Fahik
HIDUP NO.32 2019, 11 Agustus 2019