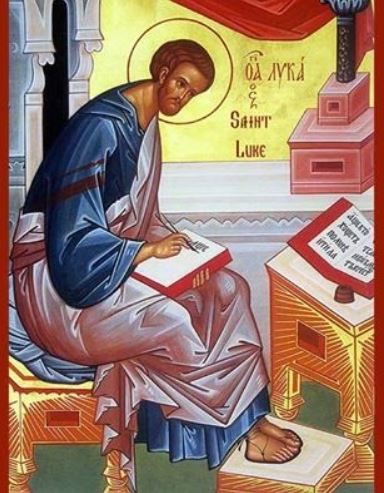HIDUPKATOLIK.com – Sudah sepantasnya, prinsip keugaharian dengan diskresi yang matang dalam terang iman, menjadi pilihan cara merayakan pesta menyambut Tahun Anjing dan Prapaskah.
Agama jangan sampai memisahkan keluarga. Komentar cukup pedas dari seorang ibu di group WhatsApp (WA) “Kerahiman Ilahi” dari sebuah paroki di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Di grup ini, terjadi pro dan kontra seputar perayaan Tahun Baru Imlek yang bertepatan dengan jumat pantang masa Prapaskah tanggal 16 Februari 2018.
“Semua keluarga saya Tionghoa dan pasti makan daging saat Sincia. Jangan sampai hal ini menimbulkan perpecahan dalam keluarga,” begitu salah satu berkomentar. Pernyataan ini sontak membuat heboh grup ini. Beberapa orang lain bahkan merasa dirugikan dengan kebijakan pastoral yang ada. Masih di grup yang sama, anggota lain ramai-ramai mengirim emoticon like. Selain itu, ada yang yang ketus berkata, “Sincia selalu identik dengan makan daging. Mari kita hormati mereka yang sudah masak.”
Ketika para pendukung sincia semakin heboh, tiba-tiba ada yang angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan, apakah sincia harus dirayakan dengan makan daging? Menurutnya, Sincia bukan soal makan daging. Kalau dirayakan dengan sukacita, maka berpantang juga sanggup dijalani.
Setelah pernyataan ini group ini menjadi sepih. Anggota lain pun berceloteh sindiran, “Pas sincia ibu mertua dan ipar saya yang bukan Katolik datang di rumah. Masa saya harus usir mereka. Atau saya minta mereka ke rumah ibu saja yah.” Celotehan ini ditanggapi salah seorang anggota grup dengan memutuskan keluar dari kelompok diskusi di WhatsApp.
Tradisi Universal
Perdebatan seputar Imlek dan Jumat pantang pertama Masa Prapaskah tidak saja meramaikan media sosial seperti WA dan Facebook. Para pastor di sejumlah paroki di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) juga dibuat sibuk dengan ragam pertanyaan. Di Paroki Hati Kudus Kramat, Jakarta misalnya, banyak ibu berkerut dahi, mencari jawaban kepada para imam soal kebijakan perayaan Imlek tahun ini di KAJ. Kekhawatiran utama adalah soal ada dan tidaknya Misa Imlek di paroki. Umat juga bertanya soal boleh atau tidak makan daging pada hari Imlek yang sekaligus hari pantang itu.
Ketegangan antara merayakan tradisi atau iman telah menjadi perdebatan panjang. Gereja dihadapkan pada perdebatan antara mengakomodasi kebutuhan umat yang merayakan Imlek atau iman. Ada kecemasan jangan sampai Gereja dianggap sudah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Di satu sisi, Imlek rupanya sudah menjadi perayaan universal. Banyak kalangan beranggapan, Imlek adalah milik dunia. Imlek tidak saja dirayakan warga Tionghoa tetapi juga warga non Tionghoa.
Dosen Liturgika STF Driyarkara, Romo Jacobus Tarigan menyebutkan, kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Tidak boleh dipaksa memihak yang satu dan menolak yang lain. Lebih utama adalah bagaiman tradisi semakin memperkaya iman seseorang. Dalam hal ini, Gereja menjadi jembatan penghubung yang baik, lewat pemahaman yang baik soal tradisi. Pertanyaan soal mana yang didahulukan kesannya “memaksa” umat Katolik untuk berpihak. Padahal tidak semua tradisi bertentangan dengan iman. “Apa saja dalam adat kebiasaan para bangsa, yang tidak secara mutlak terikat pada takhyul atau ajaran sesat, oleh Gereja dipertimbangkan dengan murah hati, dan bila mungkin dipeliharanya dalam keadaan baik dan utuh (Sacrosanctum Concilium art. 37).”
Merayakan Kehidupan
Berangkat dari sifatnya, Imlek adalah pesta rakyat. Perayaan ini harus dirayakan dalam tradisi Tionghoa. Dalam perayaan ini kehidupan itu sendiri yang dirayakan. Ada kebersamaan yang tercipta antar keluarga. Pada akhirnya, mereka memasrahkan ketakberdayaan mereka kepada Sang Pemberi Hidup. Tentu dengan harapan, agar mengalami kehidupan baru dan kesejahteraan.
Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia Romo John Rusae mengatakan, iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Manusia tidak hidup sendirian tetapi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hidup manusia, termasuk imannya, ditentukan oleh hidup sosial dan kebudayaan. Iman tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dan kebudayaan.
Gereja mengajarkan, bahwa Allah berbicara dengan bahasa manusia. Sebagai tanggapan, manusia menjawab dengan bahasa dan kebudayaannya sendiri. Gereja memanfaatkan kebudayaan untuk mewartakan Kristus, dan mengungkapkan secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan umat beriman. “Yang diharapkan adalah agar perubahan kebudayaan dalam zaman modernisasi dan globalisasi tidak dapat mempengaruhi penghayatan iman, terutama mengubah pengungkapan iman,” ujar Romo John.
Imam Keuskupan Agung Kupang ini menambahkan, Gereja telah menentukan tingkatan perayaan untuk merayakan misteri keselamatan. Ada tiga tingkatan dalam perayaan Liturgi yaitu “hari raya”, “pesta”, dan “peringatan”. Ketiga tingkatan ini bersifat universal dan lokal. Romo John mencontohkan, hari raya yang bersifat universal adalah Natal dan Paskah. Disebut universal, karena Misa Natal dan Paskah dirayakan di seluruh dunia. Ia juga mencontohkan, hari raya yang bersifat lokal adalah Misa Kemerdekaan Indonesia. Disebut lokal, karena Misa ini hanya dirayakan di Indonesia. “Apabila ingin merayakan Imlek, khususnya dalam Perayaan Ekaristi, pertama-tama perlu menentukan terlebih dahulu tingkat perayaannya. Apakah perayaan Imlek di tempat anda merupakan perayaan ‘hari raya’ atau ‘pesta’, dan Uskup setempatlah yang menentukan.”
Romo John berharap, agar perayaan Imlek disiapkan sebaik mungkin, dengan memperhatikan kaidah-kaidah liturgi. Jangan sampai karena misa Imlek, maka begitu saja memasukan simbol-simbol Imlek dalam Perayaan Liturgi tanpa dikaji. Persiapan ini sebaiknya melibatkan ahli tradisi Imlek dan diperkaya dengan terang injil.
Persiapan Batin
Fenomena perayaan Imlek selalu menjadi tema menarik. Sayangnya, banyak orang merasa Imlek adalah perayaan euforia semata. Warna merah juga selalu mendominasi perayaan Imlek. Di sini, merah bermakna kegembiraan. Namun harus diingat, jangan sampai “klenteng” di pindahkan ke gereja. Di beberapa gereja, dekorasi dipaksakan bernuansa Imlek. Dengan ini, dekorasi terkadang justru mengacaukan konsentrasi umat dan mengalihkannya dari Kristus.
Sejak Reformasi, di Indonesia digulirkan kebebasan mengekspresikan diri bagi warga Tionghoa, termasuk menghidupkan lagi perayaan Imlek. Simbol-simbol budaya Tionghoa ditampilkan tanpa ada larangan seperti sebelumnya. Imlek pun dirayakan secara besar-besaran setiap tahun.
Vikaris Jenderal KAJ, Romo Samuel Pangestu dalam kebijakan pastoral untuk umat KAJ yang dikeluarkannya menegaskan, perayaan Imlek adalah perayaan kehidupan. KAJ mengharapkan umat Allah yang masih merayakan Imlek mempertimbangkan dialog dengan budaya Tionghoa tersebut. Romo Samuel mendorong umat untuk mempertimbangkan mana yang bermakna seturut ajaran Gereja tentang pantang dan puasa, maupun tradisi Imlek. Hendaknya Imlek yang dirayakan pada 16 Februari 2018, dilakukan dengan tetap memperhatikan hari pantang dan puasa, pada hari Jumat pertama dalam Masa Prapaskah. Misa Imlek dapat dilaksanakan pada Minggu Prapaskah I.
Di Keuskupan Bogor, hari Jumat yang berbarengan dengan perayaan Imlek tetap berlaku sebagai hari wajib masa pantang dan puasa, sesuai aturan Masa Prapaskah. Hal ini disampaikan Uskup Bogor, Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM dalam Surat Pastoralnya. Mgr Paskalis meminta agar Perayaan Misa Imlek dapat dirayakan pada hari Kamis malam tanggal 15 Februari 2018 atau pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 sebelum Pukul. 12.00 WIB. “Dengan kebijakan ini tentunya menjadi jelas bagi umat dan para imam yang hendak merayakan Imlek untuk tetap menjaga keutamaan masa tobat kita.”
Tentunya paling penting adalah Perayaan Imlek tidak mengurangi makna Prapaskah. Dalam hal ini, iman mestinya menumbuhkan kepekaan. Ungkapan iman yang nyata akan tampak dalam perilaku hidup sehari-hari. Meski begitu, perbuatan itu harus tetap direfleksikan terus menerus, supaya motivasinya sungguh menjadi murni dan tulus.
Yusti H. Wuarmanuk